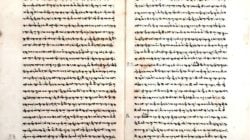Oleh: Mukhtar Tompo
Ketika menerima pesan undangan melalui aplikasi dari penggiat adat budaya, Muhlis Paraja Daeng Pajari, juga merupakan Ketua AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Kabupaten Gowa yang menginisiasi terselenggaranya Diskusi seputar adat istiadat dan budaya bertema Perluasan Partisipasi Masyarakat Adat Kabupaten Gowa Dalam Demokrasi Politik pada 9 dan 10 November 2023 di Daerah Malino, Kawasan Kaki Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, seketika itu juga saya mengingat tekad lama untuk menulis pikiran saya tentang pentingnya melestarikan adat melalui parlemen legislatif sebagai manifestasi politik yang memajukan adat, politik yang memelihara adat, berangkat dari politik nurani; politik yang beradat.
Adat bagian tak terpisah dari kehidupan Indonesia, baik setelah proklamasi, ataupun jauh ke belakang sebelum dinisbahkan oleh Patih Majapahit dengan sebutan nusantara. Indonesia merupakan maritim sekaligus agraris, dianugerahi ribuan kepulauan sekaligus bentangan pegunungan nyaris di semua propinsi hingga kabupaten, negara dengan area jutaan hektar persawahan dan perladangan juga hutan rimba belantara sekaligus surga pertambagan batu dan minyak bumi. Dengan alam seperti ini, yang dihuni lebih dari 278.353.310 jiwa (worldometers.info/worldpopulation), memiliki lebih dari 300 kelompok etnik, 1.340 suku, dan 742 bahasa dan dialek (BPS). Sangat wajar jika Indonesia disebut oleh UNESCO sebagai salah satu negara dengan adat istiadat terbanyak di dunia, khususnya di Asia Tenggara.
Adat merupakan bahasa serapan dari Bahasa Arab, Al ‘Adatu yang berati kebiasaan. Secara umum diartikan sebagai kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah atau kawasan tertentu pada kelompok masyarakat tertentu. Lazimnya manusia mempertahankan kebiasaan, begitupun dalam makna adat sebagai kebiasaan yang berhubungan dengan perayaan, ritual, atau filosofi hidup. Masyarakat adat pun tumbuh berkembang di masa lalu, kemudian mengalami pasang surut seiring berjalannya waktu, diakibatkan dua hal: 1) perkembangan teknologi dalam menjalankan kebiasaan hidup, dan 2) regenerasi yang memelihara dan mempertahankan adat kian sedikit.
Sesungguhnya adat istiadat di Indonesia sangat dipengaruhi perjalanan spiritual bangsa dari waktu ke waktu. Baik sebelum masa Islam maupun setelah masuknya, budaya masyarakat se nusantara penuh dengan ragam adat, sebab adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari kebiasaan, norma, dan hukum yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain, untuk menjaga harkat dan martabat dalam teritorial kelompok masyarakat (misal suku). Adat pun diwariskan secara turun temurun dari pengkalan-pengkalan sejarah yang masih berjalan, dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat yang masih memiliki hubungan kekerabatan dan pertautan dalam komunitas tertentu.
Dalam konteks adat di Sulawesi Selatan sendiri, khususnya Suku Makassar, selain bentuk ritual, akan selalu mengandung makna mendalam, edukasi, dan keteladanan dalam tiap-tiap bagian perayaan, seremoni, hingga kebiasaan sehari-hari. Perayaan yang masih amat kental dengan adat seperti pernikahan (abbotting), khitanan (assunna), syukuran masuk rumah baru (antama balla), syukuran akan naik haji (assuara naik hajji) atau tiba di rumah sepulang ibadah haji (assuara battu hajji), Maulid Nabi Muhammad SAW (a’maudu), dan masih sangat banyak bentuk lainnya.
Politik Beradat
Kerap kali politik disangkutpautkan dengan norma negatif, seperti ketidakjujuran, kecurangan, akal bulus, pembohongan, pembodohan, korupsi, kolusi, nepotisme, kekuasaan tan batas, dan hingar bingar keburukan lainnya disematkan. Politik itu sendiri sesungguhnya normatif dan bersifat bebas sebagai jalan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusianyalah yang merusaknya.
Dalam adat Makassar-Bugis, sesungguhnya banyak ajaran yang mendidik manusia menjadi baik, berjalan baik, berlaku baik, hingga berakhir baik, dalam mengarungi kehidupan, termasuk berpolitik. Diantaranya filosopi Appa’ Sulapa’.
Falsafah Appa’ Sulapa’ adalah suatu kearifan lokal yang diyakini masyarakat Makassar-Bugis dapat memberikan nilai kebaikan dalam hidup mereka, menjadikannya prinsip dalam perilaku dan tindakan. Appa’ Sulapa’ melambangkan “empat unsur alam” yang menjadi sifat manusia, yakni angin, air, api, dan tanah. Keempat unsur alam ini bertalian dengan “empat sisi tubuh manusia”. Paling atas adalah kepala, sisi kiri dan kanan adalah kedua tangan, dan paling bawah adalah kaki. Orang Makassar-Bugis juga melihat Appa’ Sulapa’ dalam segi pengetahuan agama Islam yaitu syariat, tarekat, hakikat, ma’rifat. Mengidealisasikan manusia Appa’ Sulapa’ menjaga prinsip keseimbangan atas-bawah (keadilan), kiri-kanan (kesetaraan). Jika orang yang memahami adat maka dia akan mengerti akan makna di balik kalimat ini ” Punna ero’ko ampabajiki tallasa’nu ri lino, isseng baji’ laloi nikanaya appaka sulapa” (jika engkau ingin kebaikan di hidupmu kenalilah dengan baik appaka sulapa’). Falsafah ini juga membawa empat unsur kehidupan yaitu Api, Angin, Air, dan Udara. Keempat unsur ini membawa sifat-sifat serta kebutuhan dalam diri manusia.
- Menjaga tanahnya (sifat tanah mengatakan), bagaimana menjaga mulut.
- Menjaga angin (sifat anginnya mencium), bagaimana menjaga pergaulannya.
- Menjaga apinya (sifat api melihat), bagaimana membuat diri terjaga dan saksama.
- Menjaga airnya (sifat air mendengar), bagaimana memilih dan menentukan perbuatannya.
Relasi Adat dan Politik
Dalam konteks bernegara, segala hal yang terjadi akan menjadi bagian dari berbangsa dan menjadi tanggungjawab negara untuk mengatur, menjaga, atau menghilangkannya, sesuai kebutuhan dan kesepakatan berkebangsaan. Begitupun dengan adat.
Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Diperkuat dengan ketentuan pasal 281 ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati dan selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain UUD 1945, beberapa Undang-undang sektoral juga memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain: 1) UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), 2) UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, 3) UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 4) UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 5) UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, 6) UU nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan 7) UU nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan.
Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat sangat penting. Fakta sejarah membuktikan jika tradisionalitas masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Meski dalam perkembangannya menyesuaikan dengan prinsip dan semangat NKRI melalui berbagai persyaratan normatif dan perundang-undangan sendiri.
Dukungan terhadap keberlangsungan adat sebagai kekayaan budaya, kekayaan intelektual, dan warisan peradaban, perlu dijaga dalam bentuk perundang-undangan hingga peraturan daerah di tingkat lokal. Selain itu juga dalam bentuk dukungan jaringan komunitas masyarakat yang heterogen agar tak terjadi benturan pemahaman ketika berbeda, karena sifat dan karakter dasar adanya adat seyogyanya menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Pelestarian adat adalah kewajiban, sebab adat istiadat adalah keniscayaan yang telah ada, menjadi bagian dari karakter bangsa yang menjaga, memelihara, dan merawat bangsa ini, Indonesia.
Makassar, 10 November 2023
* Penulis adalah Anggota DPR RI 2014-2019